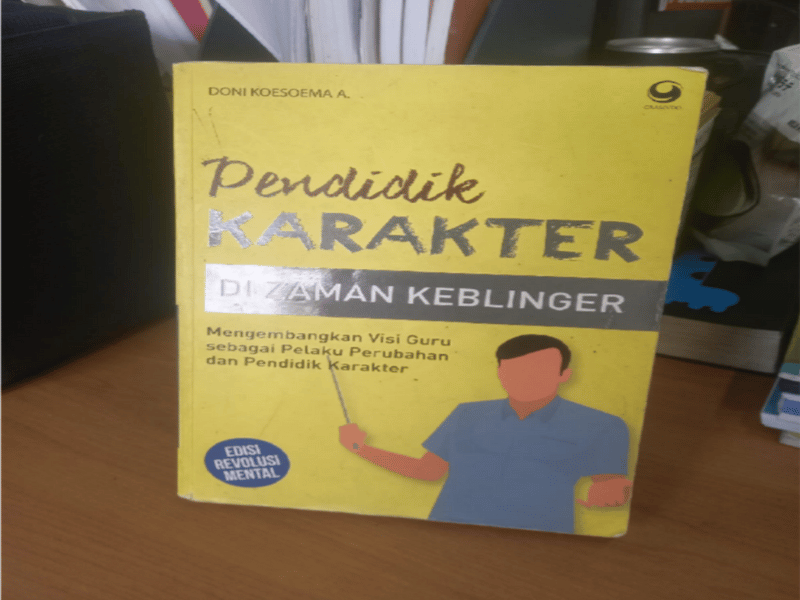Resensi Buku: Pendidik Karakter Di Zaman Keblinger
Penulis: Eduardus Laot
Secara pribadi, saya bukanlah tipe pembaca yang ulet sebab tidak setiap hari mewajibkan diri membaca buku. Namun, bagi saya, buku melebihi produk bacaan lain yang sangat bermanfaat. Sebab, dengan membaca, saya memiliki sedikit waktu untuk berdialog dengan penulis buku tersebut. Jika sehari tidak sempat membaca, maka besoknya saya mewajibkan diri sendiri untuk mampu membaca beberapa halaman yang tertunda. Bagi seorang pendidik seperti saya, buku sudah menjadi makanan pokok. Sebut saja buku paket, buku penunjang pembelajaran terkait, yang memang sering digunakan. Namun kali ini, saya tidak berhasrat untuk bercerita tentang buku paket dan buku-buku penunjang lain yang setopik.
Salah satu buku yang hari ini menarik saya ulas adalah sebuah buku kuning berjudul Pendidik Karakter Di Zaman Keblinger. Buku ini ditulis oleh seorang pendidik hebat yang hanya saya kenal lewat buku-bukunya, pendidik tersebut bernama Doni Koesoeman A. Silakan mengklik tautan tersebut jika ingin mengenal siapa sosok tersebut. {https://tokoh.id/tokoh/direktori/doni-koesoema-a/}. Pernah sekali bertemu dalam sebuah kegiatan di Sekolah Kristoforus, namun tidak sempat untuk nongkrong sebentar dengan beliau. Namun, dari konten-konten dalam bukunya, amat sangat diyakini bahwa beliau bukan orang biasa dalam pendidikan.
Secara ringkas, jika dilihat dari daftar isinya, buku ini berkisah dan beropini dari kenyataan sehari-hari tentang guru dan segala yang berkaitan dengannya. Salah satu topik yang menarik diresensi {dan seharusnya topik ini bisa dipilah menjadi satu buku lagi} adalah topik visi guru dan kejujuran akademis. Setelah saya mendalami topik tersebut, kira-kira makna harafiahnya adalah visi [kejujuran] guru dalam kenyataannya tidak mengaplikasikan kejujuran akademis yang diembannya. Mungkin agak ribet dikonsepkan dengan bahasa yang baku, namun jika dipahami, bisa jadi itu pernah dan juga mungkin sering seorang guru melakukannya.
Dalam topik tersebut, penulis memulai dengan mendeskripsikan kegiatan rutinitas guru setiap hari. Ketika masuk kelas, guru mendengarkan, mengamati, menghipotesa, dan menganalisa situasi kelas (kebersihan, kesiapan, lingkungan kelas) secara tidak sadar termasuk dalam misi seorang guru. Alasannya adalah bahwa dengan tindakan kecil itu terdapat perubahan dan perbaikan kualitas pembelajaran. Dan ini tersistem dari masa ke masa, zaman ke zaman. Beliau mengatakan demikian, model ini mirip dengan model pendidikan Jepang yang tidak pernah berubah dari zaman dahulu. Sangat menarik untuk disimak bagaimana sebuah sistem bisa merubah segala-galanya, bahkan memajukan ataupun menghancurkan kualitas sebuah peradaban bangsa.
Pendidikan di Indonesia, terutama perihal soal penilaian, bagi Doni sedikit absurd jika dikaitkan dengan model penilaian. Kita mengenal istilah KKM {Kriteria Ketuntasan Minimal}, artinya bahwa ada sebuah nilai yang disepakati bahwa di bawah nilai tersebut seorang anak dikatakan tidak selesai atau tidak lulus. Penilaian tersebut bentuknya adalah angka dan deskripsi yang menjelaskan angka tersebut (akademis). Bagi Doni, konsep ini sangat tidak jujur sebab banyak anak yang memang terpaksa harus dikatrol nilainya demi gengsi sekolah. Hal ini sangat terjadi di sekolah-sekolah pemerintah dan juga swasta. Jadi, kita sama-sama melakukan dengan tujuan yang sama. Hal ini mengaburkan kejujuran seorang penilai karena mau tidak mau, layak tidak layak, anak dimampukan. Walaupun dalam kenyataannya seharusnya belum saatnya mampu.
Permasalahan selanjutnya adalah bahwa anak pun merasa seolah-olah itu adalah haknya, hak prerogatifnya. “Ntar juga dikasih KKM. Jika KKM seharusnya dan pasti lulus. Tidak mungkin tidak lulus.” Kira-kira begitulah mental yang dibangun. Uniknya, sistem ini menciptakan manusia-manusia yang semakin menurun peradaban, lenturnya kejujuran belajar dan kemandirian sehingga tidak ada inovasi yang bisa dicapai. Penulis, Doni Koesoeman, sedikit membandingkan model penilaian dengan negara Jepang yang kurikulumnya tidak pernah diubah tetapi menghasilkan peradaban yang hebat, berbeda dengan Indonesia yang sering mengubah kurikulum hingga tidak jelas konten peradaban itu sendiri. Artinya, sistem kurikulumnya sudah dimatangkan saat mempublikasikannya sehingga tidak asal jadi, bagi Jepang.
Penekanannya lebih kepada pembentukan karakter dini saat anak masih usia TK. Saat TK, anak sudah dibiasakan untuk melakukan hal-hal ‘kotor’ seperti membersihkan toilet sendiri, kelas, meja, dan sebagainya di sekolah dilakukan sendiri. Bahkan, rentang waktu proses membersihkan toilet dan sejenisnya lebih lama dibandingkan dengan waktu belajar. Mereka belajar, namun belajarnya tidak serius. Isinya lebih kepada ‘bersenang-senang’ mengenal lingkungan dan sopan santun. Keutamaan dari pendidikan Jepang ini adalah proses tanpa peduli hasil akhir. Hasil akhir bukan sebuah masalah besar bagi mereka. Yang terpenting adalah proses dan karakter murid.
Keunikan lain adalah melibatkan orang tua dalam penilaian anak. Orang tua akan mendapat sebuah catatan atau soal praktis dan diberikan kepada anaknya di rumah. Setelah itu, hasilnya langsung dinilai orang tua. Jadi, PR-nya bukan dinilai oleh guru, tetapi oleh orang tua-nya. Maka, orang tua terpaksa harus jujur untuk memberi penilaian. Dan ini ketahuan ketika evaluasi triwulan pembelajaran oleh guru.
Saat ini, membangun kejujuran akademis tidaklah mudah dibandingkan masa lalu. Hal ini terjadi bukan karena hilangnya nilai kejujuran, tetapi kultur dan lingkungan sosial yang mendukung untuk berbuat tidak jujur soal penilaian. Contoh yang bisa ditemui adalah ketahuan mencontek cukup ditegur, menjiplak karya orang lain, mencari alasan untuk keluar dari tanggung jawab, saling menyalahkan, dan kecurangan yang dianggap harus dilakukan agar meningkatkan mutu. Semua orang tahu kesalahan, namun semuanya pada saat yang sama menerima perlakuan-perlakuan seperti itu sebagai sebuah lingkungan sosial.